"Aku lama hidup di Kota, Kota tak menentramkan hati, itulah sebabnya aku ke kampung ini. Disini aku tentram dan bahagia, Kota memang punya banyak kemewahan, tapi kemewahan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah kedamaian hati, tidak berbuat dosa tapi banyak membuat pahala".
--
Membaca Kemarau, karya A.A. Navis di tengah pekan ini membantu mengalihkan saya dari distraksi berita-berita tak mengenakkan selama seminggu penuh, kabar duka dari kerabat dekat, seorang sahabat yang juga ditinggal pergi Ibunda untuk selama-lamanya, Ibu dari anak murid suami yang juga berpulang karena covid-19, orang tua Sabahat yang belum kunjung negatif covid, serta sahabat dekat kami yang baru dikabarkan puskes kalau ia positif covid. Semua berita dalam satu pekan saja, beberapa membuat saya menangis tak henti-henti. Sisanya cukup bikin kepala cenat-cenut.
Buku ini bercerita tentang kehidupan Sutan Duano di sebuah kampung di tanah Minang. Bahkan tak diberi tahu latar lokasi wilayahnya pun, kita akan bisa dengan mudah mengetahui kalau Novel ini mengambil setting di Sumatera Barat karena gaya bercerita A.A. Navis yang "amat Minang" buat saya.
Diawali dengan kilas cepat bagaimana Sutan Duano datang ke kampung dan tinggal menetap, bekerja keras di kampung ini hingga menjadi bagian dari mereka, saking kerasnya bekerja tak henti, ia bisa dibilang cukup 'sukses' bahkan lebih sukses dari warga kampung asli, tapi suksesnya tak menimbulkan dengki, pasalnya Sutan Duano tak enggan membantu warga, memberi pinjaman yang fair, tak pernah mengambil bunga, bahkan menghapuskan sistem ijon yang jadi praktek umum sebelumnya.
Konflik berawal ketika kemarau datang. Sebuah musim yang tak bisa dihindari di Negara Tropis, Hujan berbulan-bulan, kemarau berbulan-bulan pula. Naasnya kemarau kali ini nampaknya akan tinggal lebih lama, Sutan Duano mengajak warga bergotong royong mengangkut air dari danau. Bersama-sama mengairi sawah dengan usaha mereka alih alih menunggu hujan yang tak mungkin datang di musim kemarau, ide ini tak pernah dilakukan sebelumnya. Karenanya ia dianggap gila dan masalah tak kunjung berhenti sejak saat itu.
---
Buku ini pertama kali terbit tahun 1967, sudah lama sekali sejak saya terakhir kali membaca karya sastra Indonesia tahun 60-70an, membaca buku ini rasanya bring back so many memories haha karena waktu SMP, perpustakaan sekolah saya isinya buku-buku Balai Pustaka yang kurang lebih seperti buku Kemarau pembawaannya. Tapi ini buku A.A. Navis pertama yang saya baca hehe, saya bahkan belum baca karya fenomenalnya Rubuhnya Surau Kami.
A.A. Navis nampaknya gereget sekali dengan kondisi sosial masyarakat kala itu. Banyak sekali kritik sosial yang bisa kita temukan di buku ini, mulai dari kebiasaan orang Minang yang merantau tapi meninggalkan anak istri tanpa mengirimkan nafkah bulanan, hanya datang setahun sekali membawa baju bagus lalu pergi lagi, sekalipun ada yang sukses, malah cari istri baru di tanah rantau.
Selain kondisi sosial, banyak juga kritik tentang praktek beragama yang dianggap penulis (lewat Sutan Duano) sebagai 'praktek' yang salah kaprah. Membaca Quran tanpa belajar tafsir, diibaratkan Sutan Duano bak membaca koran Inggris yang tak kita pahami isinya, atau kebiasaan membuat selamatan atau syukuran atau doa meninggal, tapi malah menambah beban tuan rumah karena harus berhutang. Belum lagi kritik pada 'penokohan', dimana Sutan Duano sendiri ingin warga tak mengikutinya karena dia Suatn Duano, tapi mengikuti prinsip dan nilai agama, siapapun yang sampaikan itu.
Apakah Sutan Duano sesempurna itu?
Hmmmmm, disini serunya, walau tak diungkap di awal, di akhir lama-lama terungkap kehidupan Sutan Duano yang jauh dari sempurna, dan kekcauan hidup Sutan Duano berawal dari respon terhadap kematian cinta sehidup sematinya, istrinya.
Secara keseluruhan saya suka sekali membaca buku ini, walau kurang sreg dengan endingnya (hehe). Bukunya tipis, 162 halaman saja. Saya selesai membaca buku ini dalam dua hari. Sepertinya berlangganan Gramedia Digital memang keputusan yang tepat yaaa haha. Belakangan saya jadi makin rajin baca buku karena buku-buku ini ada dalam genggaman.
29 Januari 2021
Asri























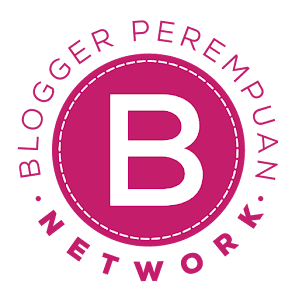
2 comments
Saya baru selesai baca buku ini dan sama, nggak suka endingnya. Kok cuma gitu doang, haha. Tapi saya pernah baca Student Hidjo dan punya ending yang sama. Mungkin mereka (penulis) menganggap ending nggak perlu panjang lebar selama inti/pesan dari cerita sudah tersampaikan semua. Jadi nggak makin bertele-tele ceritanya.
BalasHapusWah, menarik! Aku jadi penasaran sama Student Hidjo. Terima kasih sudah mampir!
Hapusleave yout comment here :)