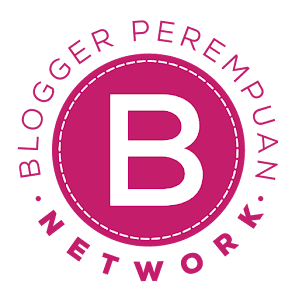Di awal tahun ini saya mendapatkan sebuah beberapa feedback yang membekas hingga hari ini. Bukan hanya membekas, feedback ini bahkan memunculkan hal terburuk dalam diri saya: menghilang dari orang-orang, hanya bertemu dengan orang-orang yang saya pilih dan tidak memberikan respon atas feedback yang saya dapat.
Awalnya saya merasa saya amat ter-trigger dengan feedback ini karena feedback ini diberikan dengan cara yang amat buruk: saya tidak diberikan clue kalau saya akan menerima feedback, bukan hanya dari satu orang; tapi tiga orang +1, feedback ini diberikan didepan anak saya (kalau saya tahu perihal ini, saya tidak akan membawa anak saya ke tengah drama kerapuhan diri Ibunya), ketiga saya merasa telah memberikan banyak hal. Di hakimi dan dipermalukan dalam satu waktu rasanya jadi poin breakdown saya beberapa bulan setelahnya.
Saya menemui seorang psikolog untuk membicarakan hal ini, saya juga mencoba bicara dengan partner saya untuk mengutarakan perasaan saya dan mempertanyakan beberapa hal yang menurut saya tidak tepat (iya, saya mencari validasi), dan beberapa bulan kebelakang, saya terus bertanya pada diri saya: why As, why was that moment hurt you so much.
Perkenalan dengan Feedback
Saya mengenal kata feedback ketika saya berada di Camp Pelatihan Indonesia Mengajar, tahun 2016. Sebelumnya saya hanya mengenal kata kritik. Ketika satu pekerjaan selesai, jika ada yang tidak beres, kritik akan diberikan, ditempat saya bekerja sebelum IM, saya hampir tidak pernah mendapatkan apresiasi dari atasan saya, jadi saya juga tidak mengenal kalau feedback ini ada dua jenisnya, baru setelah pelatihan IM saya mengenal positive feedback dan constructive feedback.
Lewat pelatihan IM dulu, saya mengenal beberapa teknik dalam memberikan feedback, juga prinsip-prinsip dalam memberikan feedback, beberapa prinsip utama seperti spesifik, disampaikan pada waktu yang sesuai (tidak terlalu lama sehingga tidak lupa pada dampak pada kejadian), memastikan bahwa yang bersangkutan tahu bahwa pada moment tersebut ia akan menerima feedback dan dipersilakan juga untuk memberikan feedback balik. Saya juga belajar bagaimana seorang pribadi seharusnya menerima feedback, seperti tidak defensif dan sebagainya.
Lepas IM, saya memulai perjalanan karier lainnya yang personel-personelnya lebih dekat ke pengetahuan tentang feedback, saya sering mendengar kritik tentang saya, dan setelah menjalani setahun perjalanan di IM dimana saya terbiasa menerima feedback dari teman-teman saya, saya jadi lebih mudah dealing with feedback. Bahkan sekarang, di tempat kerja saya saat ini, saya beberapa kali menerima feedback, sometimes it's a strong one sampai beberapa rekan kerja saya chat japri mengatakan "it's okay ya", saya malah bingung dapat japri seperti itu karena I mean it, I'm okay and took this feedback profesionally, and I know this feedback is objective. Saya malah suka mendapatkan feedback seperti ini.
Karenanya, kejadian mendapatkan feedback di hadapan beberapa orang lainnya awal tahun ini agak membingungkan buat saya, I realy took this personally, I got hurt, I feel humiliated and found myself reflecting over and over and over again "is it really a good place to grow?". Because at this moment I'm not sure.
The Feedback Challenge
Walaupun berat, saya memaksa diri saya menamatkan membaca sebuah buku berjudul Thanks for the Feedback, The Science and art of receiving feedback well* (*even when it is off base, unfair, poorly delivered, and, frankly, you're not in the mood) karya Douglas Stone dan Sheila Heen, keduanya merupakan dosen di Harvard Law School, sebelumnya mereka menulis buku Difficult Conversation (yang belum saya baca sampai hari ini walaupun sudah nangkring di Kindle).
Dari buku ini saya mengenal The Feedback Challange, tantangan feedback. Penulis tahu betul kalau feedback, terutama the negative one ini bisa memberikan sensasi tidak menyenangkan untuk beberapa banyak orang. Termasuk saya :').
Ada sebuah gambaran tepat tentang bagaimana rasanya mendapatkan negative feedback yang tidak kita inginkan:
This kind of feedback trigger us: Our heart pounds, our stomach clenches, our thoughts rase and scatter. We usually think of that surge of emotion as being "In the way"-- a distraction to be brushed aside, an obstacle to overcome. After all, when we're in the grip of a triggered reaction we feel lousy, the world looks darker, and our usual communication skills slip just out of reach. We can't think, we can't learn, and so we defend, attack, or withdraw in defeat. (page 15).
Gambaran diatas adalah gambaran yang sangat tepat tentang gimana rasanya mendapatkan feedback negatif yang poorly delivered.
Tapi, buku ini juga yang menyadarkan saya kalau perasaan-perasaan diatas adalah hasil dari trigger-trigger yang perlu kita cari tahu lebih lanjut. Karena triggers ini adalah informasi berharga, semacam peta yang bisa bantu kita menemukan masalah yang sebenarnya.
Ada 3 feedback challenge yang ditulis dibuku ini:
1. The Truth Triggers
Triggers ini terbentuk dari reaksi kognitif dan emosional kita ketika menerima feedback yang dirasa tidak tepat. Ketika kita ketrigger, kita jadi kesulitan untuk melihat sebenarnya jenis feedback apa yang sedang kita dapatkan? Apa maksud orang tersebut memberikan feedback ini kepada saya? dan kita jadi kesulitan memandang diri kita sendiri secara lebih jelas.
Triggers pertama ini mengajak kita untuk mengenal jenis feedback: Apresiasi, coaching dan evaluasi dan bagaimana ketiganya sama pentingnya untuk pertumbuhan kita secara personal. Ada panduan menarik sebelum memberikan feedback untuk menghindari truth triggers bagi penerimanya.
(i) What's my puspose in giving/receiving this feedback?
(ii) Is it the right purpose from my point of view?
(iii) Is it the right purpose from the other person's point of view?
Ini terutama bisa digunakan untuk tahu sebetulnya yang mau kita berikan tuh feedback yang mana.
Truth trigger ini juga bisa kejadian ketika penerima feedback merasa melakukan satu hal yang benar dan ditangkap secara salah oleh pemberi feedback, ada gap atau perspektif yang berbeda dari si pemberi dan penerima dalam mengolah informasi, yang~~ memang gak susah sama kalau gak diklarifikasi.
2. The Relationship Triggers
Kalau truth triggers fokusnya pada isi feedbacknya, si trigger kedua ini fokusnya pada hubungan antara pemberi feedback dan penerima.
Ada dua tipe relationship triggers.
(1) Apa yang kita pikirkan tentang pemberi feedback
Skill or judgement: How, when, or where they gave the feedback
Credibility: They don't know what they're talking about
Trust: Their motives are suspecs
Simplenya, ketika kena trigger ini, kita seringkali bertanya, "Siapa kamu ngasih-ngasih saya kritik tentang A?" atau "Duh, kamu tau apa sih?" Bisa jadi kita mempertanyakan kredibilitas mereka. Mungkin karena mereka gak punya background, pengalaman atau expertise di bidang yang sedang jadi ladang perang ini. Atau bisa jadi kita punya issue kedua: mereka punya pengalaman atau expertisnya, tapi kita gak mau jadi orang atau pemimpin yang seperti mereka. Either itu terkait gaya kepemimpinan atau values atau identitas.

Relationship triggers ini yang paling menarik buat saya karena sepertinya saya terluka karena ter-triggers disini. Misalnya buat saya, feedback tidak langsung yang diberikan kepada saya (pemberi feedback tidak hadir langsung, tapi feedbacknya disampaikan kepada saya), memberikan asumsi: "Duh ini orang punya masalah sama saya ternyata udah lama, tapi malah diam-diam dan ngomongin saya dibelakang. Maksudnya apa? mau jelek-jelekin saya?, mau saya terlihat jelek didepan semua orang".
Dan menarik sekali mengaitkan Relationship triggers ini bisa sangat bahaya karena narik lagi banyak hal-hal kebelakang. Seperti "Aduh, aku melakukan banyak banget hal yang kamu gak lakukan, bertahun-tahun, berbulan-bulan, gak dapat apresiasi yang proper sesimple ucapan terima kasih, tapi sekarang, satu kesalahan ini membuat semua orang punya hak untuk menghakimi saya secara gak adil didepan banyak orang termasuk anak saya". ---- this is an emotional notes, yang bahkan baru saya sadari ketika menuliskan post ini.
3. Identity Triggers
Kenapa feedback bisa membuat kita merasa terancam dan bikin kita gak nyaman: karena ini biasanya bikin hubungan kita yang paling penting dalam diri kita jadi dipertanyakan: hubungan dengan diri kita sendiri.
Kita seringkali mempertanyakan diri sendiri setelah mendapatkan feedback :')
Salah satu cara yang disebutkan dibuku ini jika kita merasa ketriggers dengan hal ini adalah dengan menjawab tiga pertanyaan ini:
(i) What do I feel?
(ii) What's the stroy I'm telling (and inside the story, what's the threat)?
(iii) What's the actual feedback?
Hal ini perlu kita lakukan untuk memisahkan feeling, story & feedback supaya kita bisa lebih objektif memandang feedback yang diberikan.
Ada juga satu hal yang bisa kita ingat-ingat ketika mendapatkan feedback yang dirasa menyerang identitas kita.
- Time: The Present does not change the past. The presents influences but does not determine the future
- Specificity: Being lousy at one thing does not make us lousy at unrelated things. Being lousy at something now doesn't mean we will always be lousy at it.
- People: If one person doesn't like us it doesn't mean that everyone doesn't like us. Even a person who doesn't like us usually like some things about us. And people's views of us can change over time.
What The Feedback and The book has Taught Me
Seperti yang saya bilang di awal post, feedback terakhir yang saya terima kemarin rasanya berat sekali buat saya, setelah baca buku ini saya jadi bisa mulai membedah apa sih sebenarnya trigger-trigger yang membuat saya kesulitan menerima feedback-feedback tersebut?
Relationship Triggers
Yes, trigger ini trigger yang paling besar menyita pikiran saya. Saya mendapatkan banyak feedback dari beberapa orang, uniknya ada feedback dari satu orang yang menyiapkan kegiatan ini dari awal hinggal akhir dan saya tahu betul semua feedback yang diberikan adalah feedback yang objektif. I didn't even feel hurt by her words or tears. I take it all. I am wrong. I am being irresponsible. I am a selfish bit*h that deserve this.
Tapi, hal ini gak berlaku ketika saya menerima feedback dari orang lain. Tarik balik ke penjelasan tentang triggers relationship ini, rupanya saya gak terima dapat feedback dari orang-orang yang mempertanyakan kehadiran saya ketika orang-orang tersebut juga gak sepenuhnya hadir.
Saya jadi merasa sakit hati sendiri karena saya mendapat penghakiman ketika sebenarnya "kita sama aja loh, you did not present the whole time too, sho why me? why suddenly me deserve this but not you?".
Identity Triggers
Setelah dapat feedback tersebut, hingga hari ini saya terus mempertanyakan apakah diri saya adalah orang yang sebegitu gak bertanggung jawabnya? Am I an irresponsible person? Am I an irresponsible employee? Am I an Irresponsible mother? Emosi saya begitu meluap, ditambah keresahan jadi Ibu baru yang gak tamat-tamat sampai sekarang, that moment become a big time to question myself: am I a good person?
Well, sekarang saya bisa bilang iya saya mungkin orang yang gak bertanggung jawab pada satu hal karena saya punya prioritas lain saat itu (still part of me being defensive), tapi saya merasa saya pekerja yang bertanggung jawab, dan urusan tanggung jawab-tanggung jawab yang lain, bukan urusan orang yang menghakimi saya kemarin juga. I am good, at least for my self. (took 5 freakin' month for me to answer this).
Sekarang apa?
Setelah kejadian kemarin, saya menarik diri dari banyak pergaulan. Saya bahkan menghapus instagram pribadi saya, hanya bertahan dengan instagram yang isinya review buku karena saya tetap butuh supply informasi tentang buku dan diskon buku :').

Tapi untuk kembali ke tempat saya kemarin, rasanya berat sekali. Saya sudah pernah menjadwalkan untuk kembali-- lalu tepat sehari sebelum saya harus datang secara fisik ke tempat tersebut, perut saya sakit sekali, maag saya kambuh, saya demam semalaman dan anak saya ikutan sakit. Saya menganggap ini cara tubuh saya memberikan sinyal kalau saya belum siap untuk kembali.
Namun ada satu hal yang juga luput saya lakukan karena saya terlalu sibuk dengan penerimaan diri atas feedback kemarin: saya tidak melakukan apa yang penting: follow up. Menyampaikan apa yang saya terima dan apa yang saya bisa lakukan saat ini, kalau memang tidak bisa kembali, mau rehat sampai kapan? Kalau memang menerima feedback, kenapa malah pundung (tapi yang memberik feedback sudah tahu saya akan pundung dari awal saya diberikan feedback, good for them).
Lima bulan merenungkan ini, saya merasa saya amat kekanak-kanakan hanya karena feedback yang orang lain berikan untuk saya, yang sebetulnya dampak terhadap tujuan besar yang ingin dicapainya tidak besar. Tapi ketika merasa diserang, boro-boro mikirin the grand vision, pengennya kabur aja gimana caranya bikin anak saya gak merasa terancam sama keadaan saat itu. Dan setelah menuliskan ini, saya tahu saya bukan sedang bersikap kekanak-kanakan. Saya sedang mencerna apa yang terjadi pada diri saya dan membuat saya terluka, hanya saja dalam kasus saya, butuh waktu yang cukup lama untuk mencerna hal ini.
Jadi setelah panjang lebar menuliskan curhatan saya diatas, saya akan melakukan apa yang disarankan buku ini dibagian 1/3 akhir buku: setting up boundaries.
Be transparent by telling them what burden me, being appreciative for their feedback (because yes: i learn a lot how to become present because it matters most in relationship, and being honest that I will be need some specific time to learn and unlearn some things, that I still need to digest this, that I will be back one day when I'm ready).
Ah, satu lagi; saya belajar banyak dari
feedback yang saya dapat dan buku yang saya baca:
key player dalam
feedback itu penerimanya bukan pemberinya, dalam hal ini;
saya.
I couldn't agree more with the book that we can't expect what kind of feedback we get in some specific situation. Kuncinya ada di saya. Mau tumbuh dengan
feedbacknya, atau mau hancur karena dua jam yang menyeramkan karena merasa diserang?.
Plusnya lagi: kalau kamu baca buku ini, karena tahu rasanya menerima feedback itu gimana, mungkin jadi mau mikir-mikir berkali-kali sebelum memberikan feedback supaya bisa menghindari hal-hal yang bikin feedbacknya poorly delivered.
---
Informasi Buku
Judul Buku: Thanks for the Feedback, The Science and Art of Receiving Feedback Well*
Penulis: Douglas Stone & Sheila Heedn
ISBN: 978-0-14-312713-0
Penerbit: Penguin Books
Bahasa: Inggris
Jumlah halaman: 346
Terbit pertama kali di USA, 2015
Cetakan ke: 10